Periode Orde Baru (1966–1998) merupakan salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia. Orde Baru lahir setelah runtuhnya Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno, yang kala itu dianggap gagal mengelola stabilitas politik, ekonomi, serta menjaga persatuan bangsa pasca peristiwa G30S/PKI 1965. Dengan mengusung jargon “demokrasi Pancasila” dan “stabilitas nasional untuk pembangunan”, rezim Soeharto berhasil menciptakan pemerintahan yang relatif stabil selama lebih dari tiga dekade.
Namun, demokrasi dalam kerangka Orde Baru sering diperdebatkan: apakah benar mencerminkan demokrasi sesungguhnya atau hanya menjadi kedok bagi praktik otoritarianisme? Artikel ini akan membedah perjalanan demokrasi Orde Baru dari awal kelahirannya, praktik politik yang dijalankan, peran militer, kebijakan pembangunan, hingga kejatuhannya pada tahun 1998.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Kegagalan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Sebelum Orde Baru, Indonesia telah mencoba dua sistem politik: Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Demokrasi Liberal dianggap gagal karena seringnya pergantian kabinet, lemahnya stabilitas politik, dan minimnya fokus pada pembangunan ekonomi. Sementara itu, Demokrasi Terpimpin ala Soekarno justru dianggap terlalu menitikberatkan pada kekuasaan presiden, serta membuka ruang bagi berkembangnya ideologi komunis melalui pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Krisis Nasional dan G30S/PKI 1965
Puncak krisis terjadi pada 30 September 1965 ketika terjadi kudeta yang kemudian dituduhkan kepada PKI. Peristiwa ini melahirkan kekacauan politik dan memicu aksi pembersihan massal terhadap simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Dalam situasi kacau tersebut, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kendali politik melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966). Dari sinilah jalan menuju lahirnya Orde Baru terbuka.
Konsep Demokrasi Versi Orde Baru
Demokrasi Pancasila
Rezim Soeharto memperkenalkan konsep “Demokrasi Pancasila”, yang disebut sebagai bentuk demokrasi asli Indonesia, berbeda dari demokrasi liberal Barat maupun komunisme. Demokrasi Pancasila menekankan pada:
-
Musyawarah dan mufakat.
-
Keterpaduan antara hak dan kewajiban.
-
Stabilitas politik sebagai syarat pembangunan.
-
Penolakan terhadap ideologi selain Pancasila.
Namun dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila lebih sering dijadikan legitimasi untuk membatasi oposisi politik.
Asas Tunggal Pancasila
Melalui UU No. 8/1985, seluruh organisasi masyarakat dan partai politik diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini mematikan ruang bagi ideologi lain, sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok kritis terhadap pemerintah.
Praktik Politik Orde Baru
Penyederhanaan Partai Politik
Salah satu ciri khas demokrasi Orde Baru adalah penyederhanaan partai politik. Pada 1973, partai-partai dipaksa melebur menjadi hanya tiga kekuatan:
-
Golkar (Golongan Karya) → kendaraan politik utama pemerintah.
-
PPP (Partai Persatuan Pembangunan) → fusi partai-partai Islam.
-
PDI (Partai Demokrasi Indonesia) → fusi partai-partai nasionalis dan Kristen.
Walau ada tiga partai, Golkar selalu menang besar dalam setiap pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dengan persentase suara di atas 60%. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pemilu hanya sekadar formalitas, bukan sarana demokrasi yang sesungguhnya.
Peran Militer dalam Politik
Konsep “Dwifungsi ABRI” menjadi salah satu pilar utama Orde Baru. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan keamanan, tetapi juga terjun langsung dalam pemerintahan. ABRI (kemudian TNI) memiliki kursi tetap di parlemen tanpa pemilu, serta menduduki berbagai jabatan strategis di birokrasi. Hal ini menciptakan sistem politik yang sangat militeristik dan sulit dikritik.
Kontrol terhadap Media dan Kebebasan Berpendapat
Demokrasi Orde Baru dibatasi dengan ketatnya kontrol terhadap pers. Surat kabar, majalah, atau media penyiaran bisa dibredel jika dianggap bertentangan dengan pemerintah. Kasus pembredelan Tempo, Editor, dan Detik pada 1994 menjadi bukti nyata bahwa kebebasan pers dibungkam.
Selain itu, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Aktivis mahasiswa, tokoh oposisi, hingga intelektual kerap mengalami intimidasi, penangkapan, bahkan penculikan.
Pembangunan Ekonomi sebagai Legitimasi Politik
Soeharto membangun legitimasi kekuasaannya melalui pembangunan ekonomi. Dengan dukungan modal asing dan bantuan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, Orde Baru berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang stabil pada dekade 1970–1980-an.
Keberhasilan
-
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun (1970–1990).
-
Swasembada beras pada 1984.
-
Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan sekolah berkembang pesat.
-
Turunnya angka kemiskinan dari sekitar 60% (1966) menjadi 11% (1996).
Kegagalan
Namun, pembangunan Orde Baru juga sarat masalah:
-
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela.
-
Kesenjangan sosial melebar antara elit dan rakyat kecil.
-
Perekonomian sangat bergantung pada utang luar negeri dan sumber daya alam.
-
Banyak proyek pembangunan mengabaikan hak-hak rakyat kecil (penggusuran, perampasan tanah).
Puncak Otoritarianisme
Memasuki era 1990-an, wajah demokrasi Orde Baru semakin menampakkan otoritarianisme. Aparat keamanan memperketat pengawasan terhadap mahasiswa, LSM, dan kelompok oposisi. Pemilu tetap digelar, tetapi dengan hasil yang dapat diprediksi: Golkar selalu menang telak, Soeharto selalu terpilih kembali sebagai presiden oleh MPR.
Oposisi yang Dibelenggu
Tokoh-tokoh kritis seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kerap ditekan. Bahkan ketika Megawati dipilih menjadi ketua PDI pada 1993, pemerintah berusaha menggulingkannya melalui “Kongres Medan” 1996 yang memicu kerusuhan.
Pelanggaran HAM
Beberapa kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru:
-
Tragedi Tanjung Priok (1984).
-
Operasi militer di Timor Timur (1975–1999).
-
Penculikan aktivis prodemokrasi menjelang 1998.
Semua ini memperkuat pandangan bahwa demokrasi Orde Baru hanyalah semu.
Krisis dan Kejatuhan Orde Baru
Krisis Moneter 1997–1998
Puncak kehancuran Orde Baru terjadi akibat krisis moneter Asia 1997–1998. Nilai rupiah jatuh drastis, harga-harga melambung, dan jutaan orang jatuh miskin. Ketidakpuasan rakyat meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan kelas menengah.
Gerakan Reformasi
Mahasiswa menjadi motor penggerak gerakan reformasi, dengan tuntutan utama:
-
Turunkan Soeharto.
-
Hapuskan KKN.
-
Tegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.
-
Otonomi daerah.
Tekanan semakin kuat setelah pecahnya kerusuhan Mei 1998 yang menelan banyak korban jiwa, khususnya etnis Tionghoa. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.
Warisan Demokrasi Orde Baru
Meski penuh kontroversi, Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks:
-
Stabilitas politik dan ekonomi selama tiga dekade yang memungkinkan pembangunan dasar.
-
Sistem politik terkontrol yang mematikan kreativitas politik rakyat.
-
Sentralisasi kekuasaan di Jakarta yang menimbulkan ketidakadilan daerah.
-
Militerisasi politik yang baru benar-benar dikoreksi setelah era Reformasi
Demokrasi Orde Baru (1966–1998) pada dasarnya bukanlah demokrasi dalam arti sebenarnya. Ia lebih tepat disebut sebagai “demokrasi semu” atau “otoritarianisme berbungkus demokrasi”. Dengan jargon Demokrasi Pancasila, rezim Soeharto menekankan stabilitas politik demi pembangunan, tetapi pada saat yang sama membungkam oposisi, mengontrol media, serta memanipulasi pemilu.
Meski berhasil membawa pertumbuhan ekonomi, warisan Orde Baru juga sarat dengan masalah serius seperti KKN, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM. Kejatuhannya pada 1998 menjadi titik balik lahirnya era Reformasi, di mana bangsa Indonesia kembali berusaha membangun demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
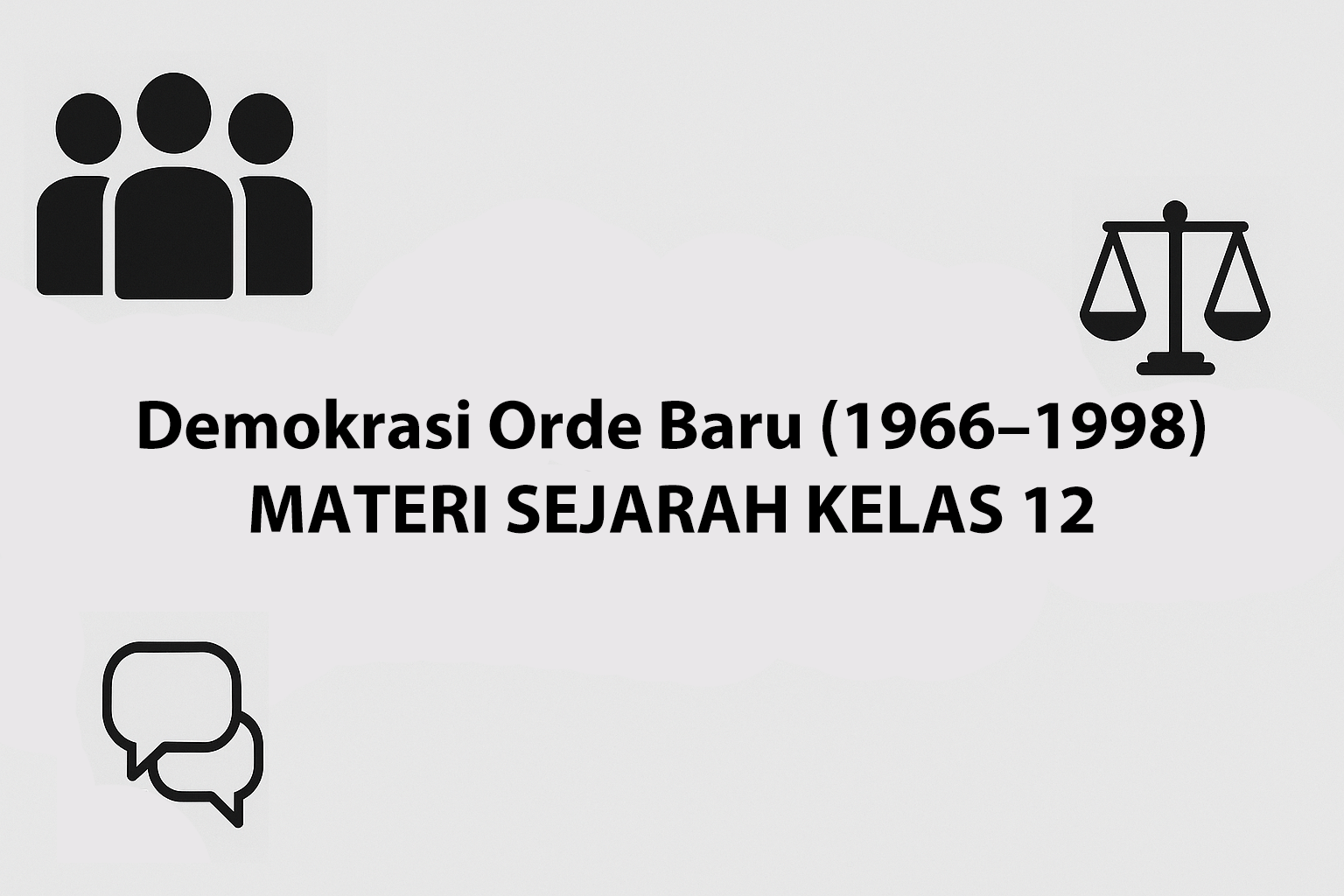
 MASUK PTN
MASUK PTN